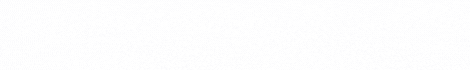Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 menjadi penanda kuat arah baru kebijakan fiskal nasional yang semakin sentralistis. Secara nasional, alokasi TKD dipangkas ratusan triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 TKD berada di kisaran lebih dari Rp900 triliun, maka pada 2026 nilainya ditekan hingga sekitar Rp690 triliun. Artinya, terjadi pemangkasan lebih dari Rp260 triliun dalam satu tahun anggaran. Kebijakan ini berdampak langsung pada daerah, terutama daerah penghasil sumber daya alam.
Di Provinsi Riau dan 12 kabupaten/kota, pemangkasan tersebut berujung pada hilangnya potensi pendapatan daerah hingga sekitar Rp6,1 triliun. Angka ini bukan sekadar penyesuaian fiskal, melainkan pemotongan nyata atas ruang fiskal daerah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan dasar.
Dengan konteks tersebut, kehilangan pendapatan sekitar akibat pemangkasan dana transfer ke daerah pada 2026 setara dengan lebih dari separuh total APBD Provinsi Riau, atau bahkan mendekati seluruh belanja pembangunan daerah jika dihitung setelah dikurangi belanja wajib. Artinya, pemangkasan ini bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi pemotongan yang secara nyata melumpuhkan kemampuan daerah menjalankan fungsi dasarnya.
Besarnya dampak pemangkasan dana transfer ke daerah akan lebih terasa jika dibandingkan dengan kapasitas fiskal Riau sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, APBD Provinsi Riau berada pada kisaran Rp9–10 triliun per tahun, dengan porsi belanja wajib seperti gaji pegawai, pendidikan, dan kesehatan menyerap lebih dari separuh anggaran. Ruang fiskal yang benar-benar bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pengendalian bencana, dan pemulihan lingkungan sangat terbatas.
Bagi kabupaten dan kota di Riau, dampaknya bahkan lebih terasa. Banyak kabupaten memiliki APBD hanya di kisaran Rp1,5–2,5 triliun per tahun. Pemangkasan dana transfer dalam skala ratusan miliar rupiah saja sudah cukup untuk menggagalkan pembangunan jalan, penguatan layanan kesehatan, hingga kesiapsiagaan bencana. Dalam konteks inilah, pemangkasan TKD 2026 harus dibaca sebagai pemindahan risiko fiskal dari pusat ke daerah, bukan sekadar efisiensi anggaran.
Konstitusi Mengamanatkan Keadilan Fiskal
Kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) 2026 menjadi problematik karena bertabrakan langsung dengan prinsip dasar hubungan keuangan pusat dan daerah. Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Prinsip keadilan inilah yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam menyusun kebijakan anggaran nasional, terutama terhadap daerah-daerah penghasil yang selama ini menjadi penyumbang signifikan penerimaan negara.
Memang harus diakui, praktik pengelolaan keuangan daerah tidak selalu ideal. Dalam berbagai kasus, peningkatan kapasitas fiskal daerah tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas tata kelola. Korupsi anggaran, pemborosan belanja, proyek infrastruktur bermasalah, hingga manipulasi pengadaan masih kerap terjadi di banyak daerah. Fakta ini sering dijadikan dalih untuk membenarkan pengetatan fiskal dan pemangkasan transfer ke daerah.
Namun, menjadikan kelemahan tata kelola sebagai alasan untuk memangkas hak fiskal daerah adalah logika yang keliru dan berbahaya. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah seharusnya dijawab dengan penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas, bukan dengan mengurangi hak konstitusional daerah atas sumber pendanaannya. Konstitusi tidak pernah mengamanatkan bahwa hak fiskal daerah bersyarat pada kesempurnaan tata kelola, melainkan pada prinsip keadilan dan keselarasan hubungan pusat dan daerah.
Idealnya, ketika daerah memperoleh ruang fiskal yang lebih besar, pengelolaan keuangan daerah harus semakin ketat dan bertanggung jawab. Anggaran harus diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar, pengurangan ketimpangan, pemulihan lingkungan, dan perlindungan kelompok rentan bukan sekadar pada belanja rutin dan proyek-proyek mercusuar. Prinsip ini sejalan dengan mandat Pasal 23 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan demikian, keadilan fiskal tidak boleh dipahami sebagai ancaman terhadap integritas keuangan negara, melainkan sebagai prasyarat bagi tata kelola yang sehat. Negara tidak bisa mengoreksi kelemahan daerah dengan cara memusatkan uang di tangan pusat. Sebaliknya, negara harus memastikan bahwa setiap rupiah yang ditransfer ke daerah dikelola secara transparan, diawasi secara ketat, dan benar-benar kembali kepada kepentingan publik.
DBH Bukan Hadiah, Melainkan Hak Daerah
Dana Bagi Hasil (DBH) kerap diperlakukan seolah-olah sebagai bantuan pemerintah pusat kepada daerah yang dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai selera kebijakan tahunan. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara tegas menempatkan DBH sebagai hak daerah penghasil, bukan sebagai instrumen diskresi fiskal pusat. Pasal 123 UU HKPD menyatakan bahwa DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dengan rumusan tersebut, hak daerah atas DBH melekat langsung pada setiap penerimaan negara yang dihasilkan dari wilayahnya.
Memang benar bahwa negara memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur keuangan negara melalui Undang-Undang APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Namun kewenangan tersebut bukan kewenangan tanpa batas. Undang-Undang APBN adalah undang-undang yang bersifat tahunan dan spesifik (lex specialis dalam konteks anggaran), tetapi ia tidak dapat digunakan untuk meniadakan atau mengurangi hak yang telah ditetapkan dalam undang-undang substantif seperti UU HKPD. Dalam prinsip hukum, undang-undang anggaran tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban secara material.
Dengan kata lain, APBN dapat mengatur besaran alokasi berdasarkan proyeksi penerimaan, tetapi tidak dapat secara sepihak memotong hak DBH daerah jika penerimaan negara dari SDA tetap terjadi. Pemangkasan DBH yang tidak didasarkan pada penurunan realisasi penerimaan, melainkan pada kebutuhan konsolidasi fiskal pusat, berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan asas keadilan fiskal sebagaimana diamanatkan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945.
Jika logika pemotongan ini dibiarkan, maka DBH kehilangan maknanya sebagai instrumen desentralisasi fiskal dan berubah menjadi alat kontrol pusat atas daerah. Negara seolah-olah mengakui hak daerah di atas kertas, tetapi mencabutnya melalui kebijakan anggaran tahunan. Praktik semacam ini bukan hanya mencederai semangat otonomi daerah, tetapi juga menempatkan undang-undang dalam posisi tunduk pada kebijakan fiskal jangka pendek.
Pada titik inilah, pemangkasan DBH tidak lagi bisa dipandang sebagai soal teknis anggaran, melainkan sebagai persoalan konstitusional tentang bagaimana negara menghormati hukum yang dibuatnya sendiri dan menempatkan daerah dalam bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Uang Dipusatkan, Beban Dilimpahkan
Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) 2026 memperlihatkan pola yang semakin menguatkan bahwa keuangan semakin dipusatkan, sementara urusan tetap didesentralisasikan. Pemerintah daerah tetap diwajibkan membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pengendalian bencana, hingga penanggulangan kemiskinan. Namun, ruang fiskalnya justru dipersempit. Ini bukan desentralisasi, melainkan pemindahan beban tanpa pemindahan sumber daya.
Lebih berbahaya lagi, praktik ini menciptakan preseden bahwa undang-undang dapat dikalahkan oleh kebijakan anggaran tahunan. Jika Dana Bagi Hasil sumber daya alam yang diatur secara tegas dalam undang-undang saja dapat dipangkas, maka kepastian hukum dalam hubungan pusat dan daerah menjadi semu. Padahal Pasal 23 UUD 1945 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk rakyat di daerah penghasil SDA.
Dalam kondisi seperti ini, daerah memang berada pada posisi yang serba terbatas. Kewenangan tetap melekat, tuntutan publik tetap tinggi, tetapi sumber daya fiskal dipangkas secara sepihak. Kepala daerah dipaksa “berinovasi” dalam keterbatasan, sementara kegagalan pelayanan publik kerap dilimpahkan kembali kepada daerah. Inilah bentuk ketidakadilan fiskal yang dilembagakan.
Namun, situasi ini tidak boleh dijadikan pembenaran bagi daerah untuk abai terhadap kualitas kinerjanya sendiri. Justru dalam ruang fiskal yang semakin sempit, daerah dituntut memperbaiki tata kelola dan mempercepat pembangunan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan publik. Anggaran harus diarahkan untuk pelayanan dasar, pengurangan ketimpangan, dan pemulihan lingkungan, bukan untuk memenuhi kepentingan elite lokal, proyek simbolik, atau kepentingan politik jangka pendek.
Desentralisasi fiskal hanya akan bermakna jika disertai tanggung jawab politik di tingkat daerah. Daerah berhak menuntut keadilan fiskal dari pusat, tetapi pada saat yang sama wajib memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada warga. Tanpa perbaikan kinerja dan orientasi pembangunan yang jelas, ketidakadilan fiskal akan terus berulang baik karena sentralisasi di pusat maupun karena penyalahgunaan kewenangan di daerah sendiri.
Desentralisasi di Persimpangan Jalan
Tekanan fiskal nasional memang nyata. Namun menjadikan daerah penghasil sebagai korban penyesuaian anggaran adalah pilihan politik, bukan keniscayaan. Jika pola ini terus berlangsung, maka yang kita saksikan bukan penguatan negara kesatuan, melainkan kembalinya sentralisme fiskal dengan wajah baru di mana pusat menguasai sumber daya keuangan, sementara daerah dibebani tanggung jawab pembangunan.
Padahal, sejak awal reformasi, desentralisasi dirancang bukan untuk melemahkan negara, melainkan justru untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah mekanisme untuk mendekatkan negara kepada warga, mempercepat pemerataan pembangunan, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Dalam bingkai NKRI, daerah bukan subordinat pusat, melainkan bagian integral dari negara yang diberi kewenangan dan sumber daya untuk mengelola urusan publik sesuai kebutuhan lokal.
Konsep ideal desentralisasi menuntut keseimbangan yang adil antara kewenangan dan pendanaan. Daerah diberikan mandat untuk membangun, mengelola pelayanan publik, dan melindungi warganya, sementara pusat menjamin dukungan fiskal yang memadai dan adil. Ketika keseimbangan ini rusak ketika kewenangan tetap didelegasikan, tetapi dananya dipusatkan maka desentralisasi kehilangan substansinya dan berubah menjadi sekadar pembagian beban administratif.
Pertanyaannya kini menjadi mendasar: apakah desentralisasi masih dipahami sebagai prinsip bernegara, atau hanya jargon yang dikorbankan setiap kali pusat kekurangan anggaran? Jika daerah terus dipaksa membangun dengan tangan terikat, maka yang runtuh bukan hanya APBD, melainkan kepercayaan daerah terhadap keadilan dan solidaritas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa keadilan fiskal, persatuan akan rapuh, dan pembangunan nasional akan berjalan timpang.