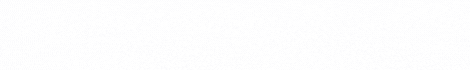Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi salah satu agenda prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Setelah satu dekade implementasi, berbagai tantangan muncul dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terutama dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, serta inovasi kebijakan di tingkat daerah.
Komite I DPD RI dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perubahan UU Pemda mengidentifikasi sejumlah isu krusial. Salah satunya adalah kebijakan moratorium pemekaran daerah otonomi baru yang perlu dievaluasi agar tetap selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menjadi aspek penting yang perlu dikaji dalam konteks efektivitas pemerintahan daerah pasca pemilu. Hasil uji materi terhadap UU 23 Tahun 2014 juga harus dipertimbangkan dalam perancangan regulasi baru agar tidak menimbulkan konflik kewenangan di kemudian hari.
Kewenangan Lingkungan dalam UU 23/2014: Tantangan bagi Daerah
Salah satu persoalan mendasar dalam implementasi UU 23 Tahun 2014 adalah penarikan kewenangan pengelolaan kehutanan dan energi dari kabupaten ke tingkat provinsi dan pemerintah pusat. Kebijakan ini membatasi ruang inovasi daerah, terutama dalam perancangan kebijakan berbasis ekologi dan keberlanjutan. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik ekologi yang unik serta kebutuhan berbeda dalam pengelolaan sumber daya alam.
Kabupaten sering kali mengalami kendala dalam mengurus perizinan misalnya asdalah izin perhutanan sosial, meskipun banyak wilayah hutan sosial berada dalam yurisdiksi mereka. Proses perizinan yang lambat menghambat masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Selain itu, ketika pemerintah kabupaten ingin membentuk Layanan Pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup untuk mendukung program mitigasi deforestasi dan degradasi lingkungan, mereka sering terbentur regulasi yang menetapkan bahwa kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah pusat dan provinsi. Akibatnya, daerah tidak dapat secara optimal mengelola sumber daya lingkungan mereka sendiri atau mengembangkan skema pendanaan inovatif yang sesuai dengan kondisi lokal.
Dalam penyusunan anggaran, daerah sering mengalami kesulitan dalam menyesuaikan kebutuhan lokal dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Regulasi seperti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 mengatur nomenklatur anggaran secara ketat, sehingga daerah yang ingin mengembangkan program inovatif berbasis ekologi atau sosial kerap terhambat oleh keterbatasan fleksibilitas anggaran. Oleh karena itu, aspek ini perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang saat ini masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI 2025, selain isu-isu lain yang menjadi dasar temuan DPD RI dikarena masalah ini menjadi isu substantif yang perlu dibahas dalam rangka menata ulang otonomi daerah secara lebih efektif
Menata Ulang Otonomi Daerah
Revisi UU 23/2014 perlu mempertimbangkan redistribusi kewenangan yang lebih seimbang agar pemerintah daerah, khususnya kabupaten, memiliki fleksibilitas dalam mengelola perhutanan sosial dan pendanaan lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Jika revisi ini mengarah pada sentralisasi yang lebih kuat, daerah bisa kehilangan keleluasaan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Hal ini tentunya sangat berisiko memperpanjang birokrasi dan menghambat efisiensi layanan publik.
Tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah juga menjadi ancaman serius. Jika revisi UU tidak menyelaraskan pembagian kewenangan dengan baik, kebijakan yang saling bertabrakan dapat menghambat efektivitas pelayanan publik. Contohnya, kebijakan fiskal yang terlalu dikendalikan pusat dapat membatasi inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
Sektor kehutanan menjadi salah satu yang paling terdampak oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengalihkan kewenangan pengelolaan hutan dari kabupaten/kota ke provinsi. Jika revisi UU ini kembali mengubah struktur kewenangan, dampaknya bisa beragam. Jika pemerintah daerah diberikan kembali sebagian kewenangan dalam pengelolaan perhutanan sosial, masyarakat di sekitar hutan dapat lebih berperan dalam perencanaan dan pelestarian ekosistem mereka. Saat ini, sebagian besar izin yang diberikan merupakan izin perhutanan sosial dalam bentuk kemitraan. Namun, jika desa ingin mengusulkan skema hutan desa, mereka menghadapi kendala dalam memperoleh modal pengelolaan. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan kewenangan, di mana kabupaten tidak memiliki wewenang untuk memberikan bantuan dana bagi pengelolaan perhutanan sosial. Di sisi lain, ada risiko bahwa revisi UU justru membuka peluang eksploitasi tanpa kontrol ketat, yang dapat mempercepat deforestasi dan memperburuk dampak perubahan iklim.
Kasus Konkret: Perhutanan Sosial dan Dana Insentif Ekologi
Salah satu tantangan utama akibat sentralisasi kewenangan kehutanan adalah implementasi perhutanan sosial di Sumatera Selatan dan Riau. Komunitas lokal telah berupaya mengelola hutan desa untuk mencegah perambahan liar dan kebakaran hutan. Namun, proses perizinan perhutanan sosial yang kini harus melalui pemerintah provinsi dan pusat menjadi panjang dan birokratis. Banyak proposal izin tertunda bertahun-tahun akibat kompleksitas regulasi, sehingga masyarakat kehilangan akses legal untuk mengelola hutan. Hal ini menyebabkan meningkatnya konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan yang mendapatkan izin eksploitasi dari pemerintah serta terhambatnya program perhutanan sosial yang seharusnya menjadi solusi keberlanjutan.
Selain hambatan birokrasi, skema perizinan PS yang ada saat ini juga memberi ruang bagi dominasi perusahaan sebagai pihak ketiga. Desa yang tidak mendapatkan dukungan pendanaan sering kali tergoda untuk menjual hak kelola mereka kepada pihak lain, yang berisiko mempercepat deforestasi di Riau. Dalam banyak kasus, skema kemitraan yang diterapkan justru mendorong desa untuk bekerja sama dengan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), yang tidak selalu sejalan dengan prinsip keberlanjutan perhutanan sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang berpihak pada masyarakat, perhutanan sosial berpotensi kehilangan esensinya sebagai instrumen pemberdayaan lokal dan perlindungan lingkungan.
Di sisi lain, Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Kabupaten Siak, Riau, merupakan contoh skema insentif bagi desa yang berkomitmen menjaga lingkungan melalui mekanisme pendanaan berbasis kinerja. Namun, sejak berlakunya UU 23 Tahun 2014, kewenangan dalam kebijakan lingkungan dan kehutanan lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah provinsi, sehingga dukungan dari tingkat provinsi dan pusat terhadap pendanaan inovatif berbasis ekologi ini masih terbatas. Meskipun kebijakan EFT terbukti efektif dalam perlindungan lingkungan, skalanya masih sangat terbatas karena kewenangan fiskal sektor lingkungan telah ditarik ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pendanaan insentif ekologi sejauh ini hanya mengandalkan reformulasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan optimalisasi sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) sebagai sumber utama pembiayaan.
Tantangan utama dalam implementasi EFT adalah pemahaman pemerintah daerah terhadap regulasi, terutama dalam mengoptimalkan perencanaan anggaran sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, daerah juga menghadapi kendala dalam mengembangkan inovasi pendanaan lingkungan, seperti pembentukan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Model bisnis yang diterapkan dalam BPDLH saat ini masih terbatas pada sektor pelayanan, sehingga kontribusinya terhadap pendanaan lingkungan belum optimal. Banyak daerah juga mengalami kesulitan dalam menerjemahkan regulasi yang ada, sehingga menghambat implementasi kebijakan lingkungan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Revisi UU Pemda bukan sekadar perubahan regulasi, tetapi keputusan strategis yang menentukan arah pelayanan publik dan kelestarian lingkungan di Indonesia. Jika tidak dikaji dengan cermat, revisi ini bisa berujung pada melemahnya pelayanan publik dan meningkatnya eksploitasi hutan. Sebaliknya, jika revisi diarahkan dengan benar-benar menyeimbangkan kewenangan pusat dan daerah, memperkuat kapasitas daerah, serta menjamin perlindungan lingkungan maka ini bisa menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan dan kehutanan di Indonesia. Pertanyaannya, Apakah daerah benar-benar siap? Apakah revisi Undang-Undang Nomor 23 bertujuan untuk menata kembali otonomi daerah agar lebih fleksibel, atau justru menjadi langkah mundur yang melemahkan semangat otonomi daerah? Mari dikawal bersama.
Keterangan: Opini ini sebelumnya sudah tanyang di Cakaplah.com