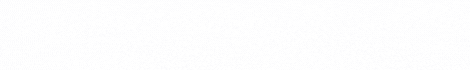Setiap tahun, belanja negara terus meningkat. Rata-rata, pertumbuhan belanja nasional mencapai 6% per tahun. Namun, dari total anggaran yang digelontorkan, hanya 27% yang ditransfer ke daerah dan desa. Sisanya sebesar 73% tetap dikelola pemerintah pusat. Angka ini menunjukkan betapa ketergantungan fiskal daerah pada pusat masih sangat tinggi, dan ruang fiskal daerah semakin menyempit.
Data terbaru memperlihatkan kontras yang semakin tajam. Pada tahun 2026, pendapatan negara diproyeksikan meningkat sekitar 10%, dari Rp2.865,5 triliun (outlook 2025) menjadi Rp3.147,7 triliun (2026). Kenaikan ini tentu menjadi kabar baik bagi APBN dan pemerintah pusat yang mendapatkan tambahan ruang fiskal untuk membiayai agenda pembangunan.
Namun, pada saat yang sama, justru pendapatan daerah dipastikan menurun. Penyebab utamanya adalah pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Di Provinsi Riau, misalnya, seluruh kabupaten/kota diproyeksikan mengalami penurunan signifikan, mulai dari 11,4% hingga 22,0%. Bagi daerah yang PAD-nya relatif kecil, penurunan ini akan menjadi pukulan keras terhadap kemampuan mereka membiayai pelayanan publik dasar.
Daerah Menjadi Garda Depan, Tapi Minim Sumber Daya
Ironisnya, beban pelayanan publik terbesar justru berada di daerah. Pemerintah kabupaten/kota harus menyediakan layanan dasar, antara 60-70% belanja daerah digunakan untuk peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, hingga penanggulangan bencana. Dengan transfer pusat yang dipangkas, mereka dipaksa berhemat dan menunda banyak program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
Kondisi ini melahirkan paradoks pembangunan. Di satu sisi, pusat menikmati kenaikan pendapatan negara. Di sisi lain, daerah yang menjadi ujung tombak pelayanan harus bertahan dengan sumber daya yang semakin terbatas. Akibatnya, kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah semakin melebar.
Di Riau, misalnya, meski menjadi salah satu lumbung migas nasional dengan kontribusi besar ke kas negara, kondisi masyarakat masih menghadapi banyak masalah. Angka kemiskinan di Riau masih sekitar 6,5%, dengan kantong kemiskinan di wilayah pesisir dan pedalaman. Tingkat pengangguran terbuka Riau berada di kisaran 5,5%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Infrastruktur dasar seperti jalan desa, air bersih, dan layanan kesehatan masih jauh dari ideal di banyak kabupaten. Dengan pemangkasan TKD hingga 22%, banyak program daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat akan tertunda atau dipangkas.
Risiko Kesenjangan Antarwilayah
Ketidakseimbangan ini menunjukkan adanya jurang fiskal antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat menguasai porsi besar dari pendapatan negara, sementara daerah harus mengandalkan transfer yang justru dipangkas. Secara nasional, Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata hanya menyumbang sekitar 15–20% dari total APBD, sisanya bergantung pada transfer pusat. Dengan pemangkasan TKD, ketergantungan ini semakin parah. Daerah tidak hanya miskin ruang fiskal, tetapi juga dibatasi dalam melakukan inovasi kebijakan karena terkekang oleh keterbatasan anggaran.
Penurunan TKD tidak hanya mengganggu keseimbangan fiskal daerah, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah. Daerah kaya sumber daya, seperti penghasil minyak dan gas, mungkin masih bisa bertahan. Namun, daerah dengan PAD rendah akan semakin bergantung pada pusat. Dalam jangka panjang, ini bisa memperdalam ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.
Riau adalah contoh nyata. Sebagai salah satu lumbung migas nasional, daerah ini justru harus menanggung konsekuensi pemangkasan TKD. Padahal, masyarakat Riau masih menghadapi persoalan klasik: infrastruktur desa yang terbatas, akses layanan kesehatan dan pendidikan yang belum merata, serta tingginya angka kemiskinan di beberapa kabupaten.
Mengapa Reformasi Fiskal Mendesak?
Kondisi ini menegaskan perlunya reformasi fiskal yang lebih adil dan berpihak pada daerah. Ada beberapa langkah yang mendesak dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu;
- pertama, Meningkatkan proporsi transfer ke daerah dan desa. Peningkatan pendapatan negara seharusnya diikuti dengan alokasi yang lebih besar untuk daerah, bukan sebaliknya.
- Kedua, Mendorong kemandirian fiskal daerah. Optimalisasi PAD perlu dilakukan, baik melalui perbaikan tata kelola pajak daerah, pemanfaatan aset, maupun inovasi pendapatan yang tidak membebani rakyat.
- Ketiga, Transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan dana daerah harus dibarengi dengan pengawasan ketat agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
- Keempat, Revisi kebijakan transfer. Formula pembagian TKD perlu ditinjau ulang agar lebih adil, tidak hanya berbasis pada kepentingan pusat, tetapi juga memperhatikan kebutuhan riil masyarakat daerah.
Menutup Jurang Fiskal Pusat-Daerah
Negara tidak bisa terus membiarkan jurang fiskal antara pusat dan daerah semakin melebar. Pusat boleh saja berbangga dengan kenaikan pendapatan setiap tahunnya. Tetapi jika pada saat yang sama daerah justru kehilangan kemampuan membiayai layanan dasar.
Jika ketimpangan fiskal ini dibiarkan, maka agenda pemerataan pembangunan hanya akan menjadi slogan. Pusat mungkin menikmati surplus ruang fiskal, tetapi daerah akan terus terjebak dalam lingkaran ketergantungan struktural. Yang paling dirugikan tentu rakyat, yang berhadapan langsung dengan keterbatasan layanan publik di daerah.
Pemerataan pembangunan hanya bisa tercapai bila daerah diberi ruang fiskal yang cukup. Kenaikan pendapatan negara seharusnya menjadi kabar baik bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bagi pusat. Karena sejatinya, pembangunan bukan hanya soal angka di APBN, tetapi tentang kemampuan daerah menyediakan layanan publik yang layak bagi warganya dan pada akhirnya, pembangunan sejati hanya bisa terwujud jika daerah diberi ruang yang cukup untuk bernapas, bergerak, dan membangun.
Penulis: Tarmidzi (Koordinator Fitra Riau)